Membangun Kesetaraan KulturalMemahkotakan Budaya Terpinggir...
DISKUSI-DISKUSI kecil di ruang kelas Pascasarjana (Wacana Sastra) Unud telah membetot saya untuk menggali tradisi-tradisi lokal terpinggir untuk memberikan pencitraan virtual setara dengan tradisi besar yang selama ini menyerbu ke seluruh plosok tanah air. Lebih-lebih bila diskusi sudah membincangkan sastra dan kebudayaan Nusantara, benar-benar keindahan filosofi ''Bhinneka Tunggal Ika'' tercermin di situ. Bahasa daerah yang dipakai medium mewahanai pun tampak sangat elegan menyentuh wilayah estetis. Dalam pada itu, nilai-nilai yang dibungkus sangat humanistis dalam kerangka pengembangan adab kemanusiaan yang oleh Rahimah Haji A. Hamid (2005), disebut sebagai tradisi yang ditamadunkan untuk membangun jiwa pendukungnya. Dengan demikian, memahkotakan budaya terpinggir dimaksudkan untuk membangun kesadaran baru demi kesetaraan kultural dalam arti memberikan ruang gerak sekaligus ruang apresiasi secara lebih luas bagi tradisi-tradisi yang selama ini dipinggirkan melalui gerakan penyeragaman kultur.
Ternyata kegelisahan dalam arti kepedulian akan tradisi terpencil itu bukan hanya terjadi di Indonesia (Unud), melainkan juga terjadi di Malaysia. Buku berjudul ''Teori dan Kritikan Sastera Melayu Serantau'' yang diterbitkan Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia Kuala Lumpur 2005 misalnya, memberikan gambaran betapa pada masa kolonial, pihak penjajah membungkam pribumi untuk tinut pada politik kekuasaan. Dikaitkan dengan politik etis yang dikembangkan Belanda pada awal abad ke-20, tampaknya penjajah Belanda pun menginginkan Indonesia berada di bawah kuasanya. Masuk akal, jika kemudian gerakan Ki Hajar Dewantara melalui Taman Siswa pada 1922 di Yogyakarta mendapat perhatian serius dari pemerintah Belanda. Pasalnya, dunia baru yang ditawarkan Ki Hajar Dewantara adalah paham kebangsaan (nasionalisme) yang digali dari akar budaya bangsa Indonesia. Jelas sekali budaya demikian, budaya yang menghormati tradisi yang berakar tunggang di bumi pertiwi Indonesia, bukan berakar di kepala kaum penjajah. Dengan demikian, tokoh pendidikan ini bukan hanya mewacanakan gerakan multikultural, melainkan juga mewujudnyatakan dalam sikap perjuangannya. Hal inilah tampaknya perlu digemakan serangkaian Hari Pendidikan Nasional setiap 2 Mei dengan pertimbangan bahwa keindonesiaan bangsa ini sejatinya ditenun dengan benang perbedaan yang membentang dari Sabang sampai Merauke.
Dalam kaitannya dengan pendidikan multikultural pad era otonomi daerah, dunia sastra tampaknya pantas diapresiasi guna mendapatkan inspirasi yang sesungguhnya sebab sastra merupakan potret masyarakat zaman. Sastra telah berhasil mendokumentasikan berbagai budaya daerah plus kearifan lokal yang melingkupi. Di Tanah Toraja misalnya, menurut Shaleh Saidi (2003:39-44) terdapat kesastraan Bare'e yang berfungsi memberikan kesenangan (rekreatif) dan pelajaran (edukatif) di samping fungsi utamanya sebagai ritual keagamaan. Kesastraan Bare'e itu umumnya berbentuk puisi ada yang berupa teka-teki (di Bali disebut cacimpedan) yang disebut wailo, ada yang menyerupai pantun yang disebut bolingoni (di Bali disebut wewangsalan), ada yang berbentuk tembang (nyanyian) yang disebut Tenke atau doddenzang (di Bali disebut Macepat), ada yang berbentuk wurake, yang hanya boleh diucapkan para pendeta untuk keperluan penyembuhan orang sakit. Di Bali yang terakhir ini biasanya dipakai oleh Balian Usaha untuk kepentingan pengobatan.
Tidak hanya itu, keterkaitan juga tampak dalam ritual agama, khususnya yang bertalian dengan tradisi agraris. Bukan hanya dalam hubungan komparasi antara kekayaan batin dengan Tanah Toraja, kekayaan batin etnis Bali pun ternyata bersinergi dengan tradisi-tradisi di daerah Padang, terutama yang bertalian dengan tradisi agraris. Dengan demikian, dasar peradaban budaya Nusantara relatif sama yaitu bermula tanah pertanian. Oleh karena itu, upacara ritual pun diarahkan ke tanah diiringi dengan mengapresiasi (menyuarakan) kesastraan demi mendapatkan panen sebaik-baiknya. Di kaki Pulau Bali, khususnya di Desa Adat Kutuh tradisi itu diterjemahkan dengan ritual masugu sebelum panen. Dalam skup yang lebih luas, upaya penghormatan dilakukan secara lebih universal melalui Tumpek Warifaga (Tumpek Bubuh, Tumpek Pengarah). Dari nama-nama itu mencerminkan betapa petani menghargai alam dengan kesadaran waktu berdasarkan ala ayuning dewasa (wariga), saat mempersembahkan sesuatu kepada Sang Pencipta berupa bubuh 'penganan yang diolah sepenuhnya dari hasil pertanian' sehingga persembahan itu diniatkan untuk mengarahkan kembali (Pengarah) para petani mengolah tanah berdasarkan swadarmanya menuju kemenangan yang berpuncak saat Galungan.
Menariknya lagi, tradisi demikian seakan menjadi ''lagu wajib'' bagi perempuan Bali sehingga tidak berlebihan jika Oka Rusmini (2003: 49) melalui puisi berjudul ''Monolog Pohon'' berdesah, ''dari akar kau ajari aku mengenal tanah/membiarkan perwujudanku menyentuh kedalamannya/ dari batang kauhancurkan perisai api/menuntunku hati-hati sementara pementasanku masih tertinggal di tanahmu...''
Wilayah ritual yang menjadi bagian keseharian wanita Bali semestinya menjadi penguat bagi mereka untuk tampil lebih percaya diri. Sebab, ritual-ritual itu merupakan banten penyadaran (baan enten) yang merupakan terjemahan dari tetuasan sastra. Pemaknaan ritual yang ditarik ke arah diri itu menjadi penting artinya sehingga kesan perempuan dipinggirkan atau di persimpangan jalan sebagaimana dituduhkan oleh STA (1996) dalam kumpulan sajaknya bisa dieliminasi. Kalau itu sudah dipahami, perempuan pun bisa bersaing tak kalah dengan laki-laki. Dengan demikian, ia tidak lagi termarjinalisasi, yang oleh STA digambarkan melalui sajak berjudul ''Bukan Makhluk Kedua''. Di situ, disebutkan, ''...Ketika pintu sekolah/Pintu masyarakat dan kebudayaan/Terbuka bagiku/Kurasakan dan kualami/Bahwa kecakapan dan kepandaianku/Tak kurang dari lelaki yang mana sekalipun...''
Begitulah, sejak zaman kolonial, telah terjadi peminggiran-peminggiran budaya pribumi apalagi di daerah pedalaman dengan maksud implisit mengagungkan budaya yang dibawa penguasa, dalam hal ini kaum penjajah. Padahal, tidak tertutup kemungkinan pendalaman secara intens budaya terpinggir itu oleh pendukungnya sangat mungkin terjadi. Dengan cara itulah mereka menerjemahkan pendidikan dalam arti memaknai tradisi-tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam konteks ini, transpormasi budaya berlangsung secara alamiah dengan memahkotakan budaya terpinggir. Tujuannya jelas untuk membangun kesetaraan kultural sehingga dikotonomi pusat dan pinggiran nyaris berimpit dalam satu garis sebab keduanya berebut posisi sesuai dengan zenithnya masing-masing.
skip to main |
skip to sidebar


sedang berpose di atas pesawat jepang yang jatuh di pulau Ahe


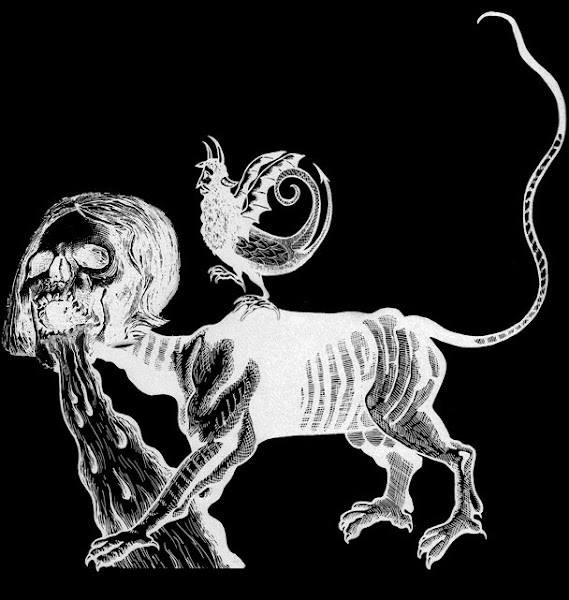
bisa saja dunia saling membonceng.
duduk natap ms dpn

DIRIKU

sedang berpose di atas pesawat jepang yang jatuh di pulau Ahe
MENGENAI SAYA

- ellya alexander tebay
- MOTO HIDUP SAYA: berjuang melawan keadaan dan mengalahkan keadaan.
SOSIAL BUDAYA
- suartawan ISI BTEMANKU
- ilustrasi 1
- karya seni1
- suta wijaya
- ART LINK
- CHUSIN lukisannya
- body paint
- lukisan koi dan buah
- piugura dan batik
- lukisan solo
- art and craft
- lukisan penjelasan
- lukisan anak
- jelasan lukisan
- catatan seni 1
- budaya rakyat
- catatan wayang
- catatan budaya 1
- KARTUNISTITS
- Potret 1 GMBR
- Potret GMBR
- cair GMBR
- santo yohanes
- Realisme
- Pramoedya A.
- Potret GMBR
SENI dan BUDAYA
LINK UMUM
KEMULIAAN
kejahatan aborsi

setang bonceng setan
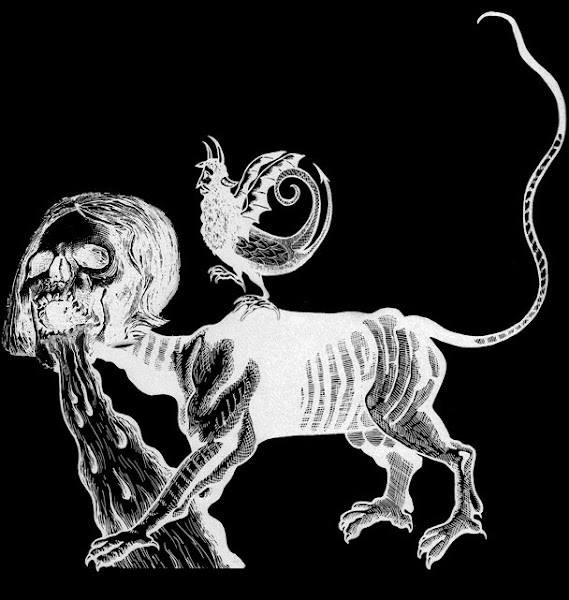
bisa saja dunia saling membonceng.



2 komentar:
salam kenal kawan, tetap lanjutkan dan tingkatkan prestasi menulis anda
maksih atas kunjungan kawan, ada banyak tulisan dan beberapa gambar sketsa yang akan saya posting. saya berharap awan bisa memberikan kmentar-komentar.=. sebagai krik maupu masukan ataupun kesan dan pesan.
Posting Komentar